Menulis: Langkah Perubahan Dalam Membangun Paradigma Baru
Pembentukan paradigma memang tidaklah mudah terlebih lagi banyaknya faktor yang membuat subjek tertentu untuk bergerak dalam sebuah perubahan. Terkadang sebuah lingkungan menjadi faktor paling kuat dan mendominasi penentuan sikap subjek tertentu. Tak salah memang dengan alasan faktor lingkungan. Hal tersebut sudah menjadi sesuatu yang lumrah dan naluriah manusia. Alasan utamanya tidak lain yakni keinginan diterimanya suatu insan dalam perkembangan ada disekitarnya (lingkungan). Dan memang tidak mudah untuk merubah hal tersebut, seperti yang dikatakan oleh Aristoteles yakni manusia adalah zoon politicon atau arti lainnya adalah makhluk sosial. Kebutuhan manusia yang utama sebenarnya bukanlah sandang, papan atau pangan sekali pun namun, kebutuhan utamanya yakni sosial, dimana manusia tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lainnya dan jika dikaitkan dengan nilai materialistis maka bahan atau alat yang dibutuhkan oleh manusia adalah interaksi.
Jika sandang akan menghasilkan cocok atau tidak, papan menghasilkan nyaman atau tidak dan pangan menghasilkan mengenyangkan atau tidak, maka interaksi akan menghasilkan ‘dipengaruhi’ atau ‘memengaruhi’. Sebenarnya hasil dari interaksi ini pun bukan menjadi hasil akhir namun akan berujung pada eksistensi insan akan keberadaannya. Kalau interaksi yang dibangun mengarah pada ‘dipengaruhi’ maka eksistensi manusia tersebut akan memberikan posisi mainstream yang hanya mengikuti eksistensi manusia lain. Namun, jika interaksi yang dibangun mengarah pada ‘memengaruhi’ maka eksistensi manusia tersebut akan menjadi subjek dalam sebuah lingkungan dan membuat eksistensi manusia lain menjadi objek.
Terkadang manusia lebih peduli akan posisinya dalam sebuah masyarakat atau lingkungan dengan tidak melawan budaya telah dibangun. Tetapi, suatu hal lucu dengan mengingat apa yang dikatakan Gie yaitu “lebih baik saya diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan”. Andai semua manusia menyadari akan perkataan itu maka mungkin kemampuan standar sosial pada masyarakat akan berubah drastis. Sebenarnya jikalau manusia hanya mengkhawatirkan posisi serta eksistensinya maka ada pertanyaan lain yang benar-benar mempertanyakan eksistensi yakni “Bagaimana cara agar disaat kita mati nanti, namun akal tetap ada atau hidup?”. Pertanyaan itu akan sulit untuk ditelaah terlebih dulu namun sebenarnya jawabannya sangatlah mudah.
Menulis, dengan menulis membuat akal kita tetap ada atau hidup. Sehingga segala bentuk eksistensi yang diinginkan oleh manusia dan dituliskan maka akan tetap ada. Memang secara fisik akal pun telah mati didalam otak manusia, namun yang menjadi perlu dipahami adalah akal akan disebut akal jika kita dapat digunakan untuk berinteraksi atau lain sebagainya. Hal ini terkait akan akal inilah sebenarnya yang akan menjelaskan eksistensi atau keberadaan manusia.
Untuk mempertahankan hal tersebut pun maka perlu dibahasakan ke dalam aksara tertentu. Sebenarnya sudah banyak contoh bahwa akal manusia yang telah mati masih hidup seperti, H.O.S. Tjokroaminoto yang memperkenalkan akalnya melalui buku yang ditulisnya yaitu ‘Islam dan Sosialisme’ kemudian ada Tan Malaka yang menulis ‘MADILOG’ lalu ada Plato dengan mahakaryanya ‘Republik’. Keberadaan akal mereka sebenarnya masih hidup atau ada namun hanya sedikit yang mengakui keberadaannya yakni manusia yang tidak membaca apa yang mereka tuliskan.
Maka dengan menulis pun sebenarnya menjadi suatu hal yang sudah lama dalam meningkatkan eksistensis manusia namun memang hanya sedikit yang paham akan keberhasilan menulis dalam mengadakan akal yang telah mati atau menjadikannya alat eksistensi dalam sebuah sosial. Jikalau ingin hidup maka hidupkan dengan suatu langkah perubahan yang akan menjadi paradigma masyarakat yang baru sehingga hal ini pun juga dapat menjadi bentuk produktivitas dalam meningkatkan kualitas standar dalam bermasyarakat. Jikalau kita bisa lihat, minat baca di Indonesia pun sangat kecil terbukti dari studi yang dilakukan oleh Central Connecticut State University bahwa Indonesia menduduki peringkat 60 dari 61 negara objek penelitian. Terlebih lagi didukung dengan tradisi menulis yang lebih rendah ketimbang membaca dan data berupa sebesar 3,56% penduduk Indonesia yang buta aksara atau setara dengan 5,7 Juta penduduk dari tahun 2015.
Penulis : Andi M.Z. Taufik (Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta)








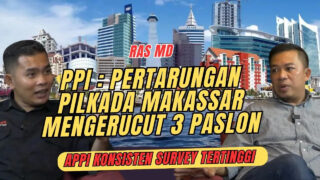


















Tinggalkan Balasan