Rahasia Cinta di Antara Pandemi Covid 19 dan Sikap Keberagaman
Atas nama agama, juga demi tanggung jawab kekhalifahan, “jalan politik” merupakan pilihan paling awal penyebarluasan ajaran Islam. Itulah fakta di zaman itu. Sebagai jalan politik, Islam menawarkan keselamatan melalui unjuk rasa kekuasaan. Dakwah merupakan tindakan politik. Pendirian masjid pun merupakan agenda politik. Bahkan doa-doa dalam khotbah pun menjadi begitu politis.
Nah ketika Islam makin kental unsur politiknya, substansi Islam pun mengalami kemunduran. Kekuasaan Islam menjadi superior di atas rasionalitas Islam. Agama menjadi lebih politis, dan rasionalitas agama makin terpinggirkan.
Untungnya, pada periode selanjutnya terjadi pertemuan mesra antara teologi Islam dengan filsafat pra-barat dan timur. Pertemuan mereka melahirkan generasi pemikiran yang lebih terbuka dan inklusif. Agama tidak lagi menjadi satu-satunya kebenaran yang bersifat absulot. Agama dengan begitu rendah hati menerima kebenaran justru dari pihak-pihak yang memprotes warisan agama sebelumnya.
Dalam konteks ini, kaum sufi ingin mengembalikan agama pada substansinya. Agama adalah bahasa cinta universal yang dimiliki semua manusia. Ungkapan Masyur sang Nabi : “ummati… ummati… ummati”, merupakan bahasa agama yang memanifestasikan cinta tanpa batas. Maka, cinta seorang sufi yang memabukkan dirinya sendiri, justru merupakan cinta yang salah alamat.
Sebagain sufi, memang hanya sampai pada tahap keterpesonaan tajalli Tuhan pada keseluruhan dirinya. Namun mereka tidak mengganggu kehidupan orang-orang di sekitarnya.
Bandingkan, bila situasi yang sama juga terjadi dalam diri seorang politisi muslim. Maka kekuasaan absulot agama di tangan mereka akan selalu menghadirkan malapetaka demi malapetaka. Sementara, logika absulot di imajinasi dan pemikiran kaum filsuf, justru menciptakan arogansi-arogansi intelektualitas.
Mau pilih mana?
Harus diakui, saat ini agama hanya menjadi monopoli sebagai elit. Agama menjadi begitu despotik. Agama kehilangan fungsi emansipasinya. Mengapa ini bisa terjadi?







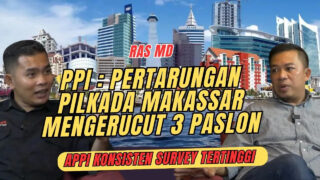
















Tinggalkan Balasan