Rahasia Cinta di Antara Pandemi Covid 19 dan Sikap Keberagaman
Ya, seperti saya katakan sebelumnya. Bahwa watak agama yang politik dan rasional, justru menjadi “beban” mengembalikan substansi ajaran agama yang sejati.
Benarkah, agama dalam buku Murthada Murtahari merupakan ekspresi keagamaan yang lebih tinggi daripada agama di hati seorang petani miskin yang bodoh? Benarkah gagasan empat perjalanan Mulla Shandra jauh lebih utama dibandingkan dengan “pengorbanan cinta” seorang migran yang meninggalkan keluarga dan kampung halamannya?
Benarkah kontribusi keilmuan Ibnu Sina, Ibnu Batutah, Al-Ghazali, Sir Muhammad Iqbal, Abeed Aljabiri jauh lebih penting di mata Allah dibandingkan kontribusi kecil relawan literasi di pelosok-pelosok desa?
Benarkah, cinta sayyidah Fatimah dan Sayyidah Khadijah kepada Nabiullah Muhammad, jauh lebih besar dan agaung di hadapan Allah, dibandingkan bacaan salawat seorang nenek tua yang tak bisa membaca Al-Quran?
Bila jawaban kita, adalah “ya” maka itu merupakan cerminan bahwa betapa agama telah kehilangan cinta yang sederhana. Agama yang mengarusutamakan logika dan kekuasaan, menyeret kita pada kesadaran hirarkis. Sebuah kesadaran yang melebihkan “sebuah kebaikan” lalu cenderung mengabaikan bahkan meremehkan kebaikan yang lebih kecil.
Samakah “nilai” kebaikan dalam pandangan manusia dan pandangan Tuhan? Dalam konteks ini, kaum sufi merupakan tulang punggung menemukan jawaban.(*)







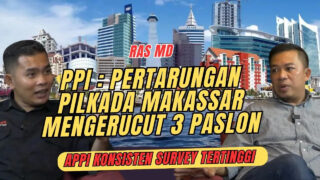

















Tinggalkan Balasan