Kebebasan berekspresi Sue: Luka yang Belum Sembuh di Papua
Oleh Marselino W Pigai – Koordinator Grup Aksi Amnesty Papua.
“z (saya) sakit, dapat pukul itu belum sembuh, seperti hari in (ini) lagi masih oo”. Tanya saya, beratnya di bagian mana ee? z (saya) sakit seluruh badan in (ini), juga kepala in (kepala) yg (yang) susah jalan in (ini). Begitu kalimat ekspresi jeritan yang diceritakan Sue (menggunakan nama anonim) kepada saya dalam sebuah pesan melalui Media sosial yang dikirim pada Rabu, 4 September 2024, 05.35 Waktu Papua.
Sakit ini belum selesai dan sembuh akibat pemukulan, interogasi selama kurang lebih 4 jam. Sue diperlakukan tindakan tidak manusiawi oleh aparat keamanan yang diduga empat orang; dua Brimob dan dua polisi dalam sebuah mobil brimob tertutup yang diangkut setelah penangkapan di Siriwini (jalur masuk KPR Siriwini) pada kegiatan aksi demonstrasi tanggal 15 Agustus 2024.
Sue ditangkap didepan penulis, aparat menargetkan tapi luput dari penangkapan termasuk penulis (sebagai konses dan aktivis kemanusiaan) dan kawan-kawan yang terlibat dalam aksi demonstrasi secara damai, memprotes New York Agreement yang ditandai cikal bakal termasuk menerapkan paradigma rasialis terhadap Bangsa Papua. Adanya pengabaian hak orang asli Papua sebagai subyek hukum dalam proses perumusan dan pembahasan sampai persetujuan pada 15 Agustus 1962 di New York. Juga, bulan Agustus memiliki rekaman kemarahan bangsa Papua terhadap perspektif Rasisme. Karena itu menandai Agustus sebagai bulan rasisme.
Korban dan rusaknya demokrasi
Derita dan jeritan Sue harus dilihat dari perspektif yang lebih luas dalam kaitannya dengan geraka
jalannya demokrasi Indonesia. Indonesia sendiri adalah negara yang digembar-gemborkan mempunyai tradisi dan sistem demokratis. Demokrasi tidak hanya urusan politik praktis pemilu. Demokrasi juga menempatkan Kebebasan berekspresi dan berpendapat, setidaknya sebagai elemen yang substantif dalam mengukur iklim sistem demokrasi. Karena itu kebebasan berekspresi dan berpendapat ikut menandai berjalan maju-mundur, ada tiadanya atau hidup dan matinya sebuah demokrasi.
Tindakan pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat justru mencitrakan kontestasi demokrasi Indonesia yang buruk di mata publik termasuk wilayah yang lebih luas di level dunia. Republika.co.id, 2023 merilis bahwa pada kesimpulannya, indeks kebebasan berekspresi dan berpendapat belum ada perkembangan signifikan pada masa kepemimpinan Jokowi periode kedua, bahkan justru menurun. Kesimpulan itu disampaikan berdasarkan hasil kajian selama lima tahun terakhir oleh Lembaga SETARA Institute bersama INFID.
Berikut penjelasan yang dikutip Republika.co.id, 2023: “Kalau dibandingkan dengan akhir periode pertama Jokowi yang mencapai 1,9 atau tidak pernah capai angka dua, dan angka itu selalu turun terus-menerus,” kata peneliti SETARA Institute Sayyidatul Insiyah di kawasan Menteng, Jakarta, Ahad (11/12/2023). Laporan lain, Amnesty Internasional Indonesia menerbitkan dengan judul Meredam Suara, Membungkam Kritik Tergerusnya Kebebasan Sipil di Indonesia. Secara khusus pada halaman 51, setidaknya mencatat rekaman kekerasan fisik dan pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat di Papua.
Jika mengingat kembali (seperti juga tercatat dalam laporan yang sama, Amnesty Internasional Indonesia) pada September 2019, ada gelombang gerakan yang melakukan demonstrasi melibatkan ribuan mahasiswa, serikat buruh, aktivis, dan kelompok masyarakat sipil lainnya memberikan sinyal peringatan terhadap kemunduran demokrasi di Indonesia. Karena gerakan itu merespon demokrasi secara umum tetapi sub elemen kebebasan berekspresi dan berpendapat menjadi problem berikutannya.
Demokrasi Indonesia menurun, artinya tidak sedang baik-baik atau menjadi sakit atau buruk. Sakitnya demokrasi diakibatkan karena sakit hati dan pikiran manusia. Kesakitan demokrasi karena kesakitan manusia yang menghidupkan demokrasi. Maka esensinya demokrasi itu manusia, martabat manusia. Karena itu Jeritan kesakitan Sue memiliki korelasi yang kuat dengan kontestasi demokrasi dalam kaitannya dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat di muka umum di Papua yang dampaknya pada level Indonesia.
Menegakkan atau Menabrak aturan?
Sakitnya Sue diakibatkan karena sakitnya kebebasan berekspresi dan berpendapat. Kesakitan itu hadir karena saluran ekspresinya dibatasi bahkan disumbatkan. Kemanan nasional ataupun keamanan Kamtibmas di lingkungan dan saluran jalan yang digunakan masa aksi demonstrasi terganggu lalu lintas. Itu menjadi pilihan dalil-dalil yang dipergunakan aparat keamanan kepolisian. Alasan semacam itu kerapkali belum ditunjukkan ketika tanpa negosiasi dibubarkan paksa, misalnya titik Aksi Kalibobo dalam kasus penangkapan Sue.
Alasan itu manjadi tonggak penting mendudukkan aksi harus dibubarkan. Karena itu saluran-saluran ekspresi pikiran dan hati nurani belum sehat dihadapi Indonesia dan Papua. Manusia disakiti misalnya aksi dalam kasus Sue, ada korban lainnya terkonfirmasi mengalami kejadian pemukulan, distrom, dirotan bahkan ditembak peluru karet dan peluru tima. Titik Aksi Siriwini, kelompok Sue ada 8 (delapan) orang yang korban. Satu diantaranya kritis. Di titik lainnya, seperti Karang Tumaritis ada dua orang korban tembakan peluru karet yang mengenai tubuh bagian paha dan lainnya.
Menurut kesaksian Korban, penangkapan, selama dalam perjalanan pengangkutan kendaraan terutama titik Aksi Kalibobo, mendapatkan pemaksaan diam dengan pemukulan rotan, ketika menyanyikan yel-yel. “Kami menyanyikan yel-yel ‘kami bukan mera putih, kami bintang kejora’, polisi menyuruh diam, pukul pake rotan”. Setiap kali menyanyikan yel-yel, polisi memukul dengan rotan sampai di Polresta Nabire”. Kata Yako salah satu masa aksi yang menjelaskan kepada penulis pada saat menanyakan kejadian melalui telpon seluler pada tanggal 16 Agustus 2024.
Adakah hukum yang membebaskan?
Jika ekspresinya disalurkan dengan benar pada ruangnya, jeritan Sue belum akan ada. Atau mencapai penumbuhan dari sisi kedudukan demokrasi dan kebebasan berekspresi dan berpendapat di Papua. Saluran yang tersumbat karenanya memaksakan kesakitan. Aparat keamanan kepolisian resor Nabire juga mengekspresikan mode penerapan dan menduduki kebebasan berekspresi adalah sesuatu yang seolah-olah menakutkan kedudukan negara. Perspektif itu menjustifikasi gerakan demonstrasi diseret kedalam pemahaman gerakan yang dilarang.
Karena itu negara dalam wilayah praktek hukumnya berusaha mematikan pikiran dan perasaan mati sebagai manusia yang secara tubuhnya hidup. Bagaimana mungkin tidak akan disebut demokrasi yang tidak pingsan di Indonesia? Karena itu supaya berjalan dan mematikan berjalannya kebebasan demokrasi khusus berekspresi dan berpendapat, diperlukan peraturan perundangan yang harus bisa memastikan juga peraktek dan penggunaan kekuatan aparat keamanan yang tidak berlebihan dan menghormati kebebasan berekspresi dan berpendapat secara damai sesuatu peraturan yang berlaku.
UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 25 UU memastikan, setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara memenuhi sesuai undangan-undangan, seperti diatur UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28E ayat 3 menegaskan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Kebebasan berpendapat di Indonesia sudah merupakan sebuah hak yang dilindungi oleh konstitusi.
Karena itu Kebebasan berekspresi dan berpendapat di muka sekurangnya dijamin UU No 39 tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum. Sejalan juga dengan deklarasi hak asasi manusia di tingkat internasional. Seperti diatur melalui pasal 19 konvenan internasional tentang hak Sipil dan Politik, mengatur hak atas kebebasan berekspresi, pasal selanjutnya pada pasal 21 mengatur hak kebebasan berkumpul, termasuk pasal lainnya pada pasal 22 mengatur kebebasan berserikat.








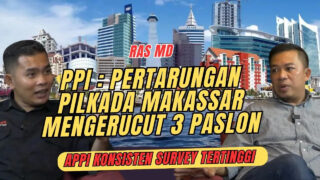


















Tinggalkan Balasan